Digital
merupakan penggambaran keadaan menggunakan bilangan biner dengan bantuan mesin.
Berkat perkembangan pengetahuan manusia, digital berkembangan menjadi sebuah teknologi
canggih. Ada dua jenis teknologi yang berkembangan yaitu transmisi informasi
dan otomisasi komputer. Hasil konversi antara dua teknologi ini melahirkan
teknologi informasi (TI) yang kemudian mengubah cara manusia bekerja dan
berinteraksi.
Dewasa
ini, perkembangan dunia digital telah melahirkan sebuah ruang baru yang
bersifat maya. Pada awalnya ruang maya (yang disebut virtual reality) diciptakan
TI untuk mempresentasikan ruang fisik. Saya membayangkan pembentukan ruang maya
ini secara sederhana terjadi ketika kita berada di depan cermin. Diri kita yang
berada dala cermin merupakan representasi diri kita. Sifat eksistensi kita
dalam cermin bersifat maya. Artinya kita benar-benar tidak berada dalam cermin.
Gambaran diri dalam cermin merupakan reflection diri kita dalam ruang
fisik. Jika kita menyisir dan membelai rambut dalam ruang fisik maka refleksi
diri dalam cermin akan melakukan hal yang sama. Apa yang terjadi dalam cermin
ini masih bersifat sederhana. Dalam lingkup digital, refleksi diri kita itu
melibatkan proses pemrograman yang rumit yang melibatkan kerja-kerja mesin
sesuai dengan perintah (souerce code) yang ditulis. Akibatnya, data yang
membangun ruang maya menarik pengguna menjauhi tubuhnya sendiri. Yang lebih
parah, dalam ruang maya ini, kita mengalami dunia tak terkendali tanpa batas di
mana kita tidak bisa mengendalikan apapun yang kita kehendaki.
Term
virtual reality pada tempat tertentu disebut sebagai contraditio in
terminus. Istilah kenyataan/realitas maya oleh pencentusnya disebut cukup
ganjil dan kontradikstoris. Banyak pengkritik kemudian menuliskan bahwa
realitas virtual sebagai ruang baru itu tidak pernah bisa mempresentasikan
kenyataan (ruang fisik). Pendapat ini disindir oleh Castells dengan menyebut
sebagai mereka yang secara implisit merujuk pada pengertian primitif yang
absurd. Menurutnya, kekhasan Teknologi Informasi tidak terletak pada
kemampuannya untuk merefleksikan realitas virtual ke dunia fisik melainkan
kemampuannya untuk membangun kemayaan yang nyata (real virtuality). Dari
perkembangan TI yang demikian ini, kita tidak lagi membayangkan sebuah ruang
virtual sedehana yang hanya berfungsi merefleksikan kenyataan seperti berdiri
di depan cermin tetapi lebih dari itu ia mampu menghadirkan kemayaan yang
nyata. Ini berarti TI mampu menghadirkan efek suatu peristiwa atau entitas
secara aktual meskipun peristiwa atau entitas tersebut tidak real. Misalnya, TI
mampu menghadirkan efek aktual dari peristiwa orang yang menyisir dan membelai
rambut secara virtual. Dalam ruang fisik tidak ada orang yang sedang menyisir
dan membelai rambut, tetapi orang itu merasakan ada efek aktual secara real
terjadi atasnya.[1]
Perkembangan
TI yang yang semakin canggih ini kemudian membawa kita dalam sebuah refleksi
tentang ruang baru yang disebut cyberspace. Dalam cyberspace, TI
bukan hanya mengomunikasikan pengalaman tetapi menjadi pengalaman itu sendiri. Cyberspace atau biasa disebut sebagai
ruang virtual atau ruang siber merupakan satu ruang publik baru yang bisa
diandalkan untuk melakukan apapun secara artifisial. Cara artifisial adalah
cara yang mengandalkan pada peran TI, khususnya teknologi seperti komputer. Kehadiran
cyberspace telah mengalihkan berbagai
aktifitas manusia (politik, ekonomi, sosial, kultural, spiritual, dll.) dari
dunia nyata (ruang fisik) ke dalam dunia virtual (ruang virtual) dalam bentuk
kehidupan artifisial. Ini berarti orang tidak hanya lagi berhadapan dengan
piranti teknologi tetapi membenamkan seluruh seluruh indera dan tubuhnya ke
dalam lingkungan baru yang dibangun oleh komputer. Hal ini bisa terjadi karena
kemayaan yang terjadi dalam ruang virtual mampu menghadirkan berbagai
pengalaman baru dengan derajat realisme tanpa batas.
Sebagai ruang publik baru, Cyberspace memiliki
pengaruh terhadap kehidupan sosial manusia yang tampak dalam tiga tingkatan,
yaitu tingkat individual, tingkat antarindividual dan tingkat komunitas. Pada
tingkat individual, cyberspace
mengubah pemahaman kita tentang “identitas.” Ini berarti di dalam ruang siber
tejadi kekacauan identitas karena setiap orang yang berada di dalamnya dapat
memainkan berbagai peran sesuai dengan keinginan tanpa terikat identitas asli.
Pada tingkat antarindividual, cyberspace menciptakan
relasi sosial yang bersifat virtual di ruang-ruang virtual. Relasi ini tampak
jelas dalam virtual shopping, virtual
game, virtual conference. Pada tingkat komunitas, cyberspace dapat menciptakan satu model komunitas demokratis dan
terbuka yang disebut sebagai komunitas imajiner. Di dalam komunitas imajiner
ini, setiap orang bisa menjadi pengontrol bagi dirinya.[2]
Kehadiran
ruang siber dengan segala kemampuan seperti ini sangat mudah terkooptasi oleh
hegemoni kekuasaan. Dalam sejarahnya, penggunaan internet (interconnection
Networking) bermula sebagai sistem komunikasi militer Amerika Serikat untuk
mengedarkan informasi rahasia. Ketika dunia bisnis melihat kemampuan
komersialnya, internet digunakan untuk melayani hegemoni kapital. Akhir-akhir
ini, internet kemudian dikooptasi oleh hegemoni politik yang rentan digunakan
untuk kepentingan oligark. Kehadiran fenomena baru dalam dunia digital ini pada
akhirya membawa kita masuk dalam era post-truth di mana orang tidak lagi
percaya pada kebenaran akan fakta-fakta objektif.
Kamus
Oxfrod mendefisinikan istilah ini sebagai suatu keadaan di mana orang lebih
menanggapi perasaan dan keyakinan dari pada fakta-fakta objektif.[3] Imbas dari hadirnya post-truth,
kita tidak lagi mampu membedakan dengan jelas antara fakta dan hoaks.
Berbagai informasi palsu dapat dengan mudah diproduksi dan disebarkan secara
masal berkat bantuan teknologi digital dan internet. Dampak yang ditimbulkannya
tidak hanya menyerang masyarakat menengah ke bawah tetapi juga menjangkau
masyarakat akademis. Di samping itu, era post-truth menghasil disrupsi
yang menyerang semua sisi kehidupan manusia seperti ekonomi, pendidikan, agama,
sosial dan politik. Akibatnya, banyak orang kehilangan pekerjaan karena manusia
tidak lagi dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan operasional yang sekarang sudah
diambil alih oleh kerja mesin.
Fenomena
di atas pada satu sisi secara positif bermanfaat dalam mempermudah semua
pekerjaan manusia namun pada sisi lain bisa melahirkan kegetiran yang mendalam
terhadap eksistensi manusia. Menurut saya ada dua aspek menonjol yang bisa
digambarkan untuk memahami bagaimana fenomena dunia digital yang berkembang dalam
ruang virtual, yaitu hegemoni kapitalis dan hegehomi oligarki.
Pertama,
dalam
kaitan dengan hegemoni kapitalis. Sejarah dunia telah mencatat terjadinya
ekspansi kapitalis dari ruang privat ke ruang publik. Ketika ekspansi ini
terjadi, ruang publik akan mengalami krisis. Hana Arendt melukiskan krisis
ruang publik itu ditandai oleh sejarah komersialisasi di mana seluruh realitas
ruang publik tunduk di bawah logika produksi dan konsumsi sebagai objek
komoditas dalam pasar kapitalis.[4] Menurut saya, ekspansi
kapitalis ini tentu akan bergerak masuk ke dalam ruang virtual dan pada
gilirannya akan melahirkan krisis global yang luar biasa. Krisis yang kita
rasakan sekarang adalah terjadinya disrupsi dalam segala bidang. Salah satu
contoh adalah munculnya aplikasi traveloka yang mematikan sebagian besar agen
penjualan tiket offline. Begitupun juga dengan munculnya aplikasi-aplikasi
serupa seperti Gojek dan Grab menghasilkan dampak yang sama. Dalam bidang jasa
keuangan, munculnya aplikasi yang menerapkan sentuhan teknologi
modern yang dikenal dengan sebutan Fintech (financial
technology). Teknologi ini memudahkan semua
aktifitas keuangan dan pada gilirannya akan menggeser semua kerja manusia.
Jika ditarik
kebelakang, kita akan menemukan sekumpulan kapitalis yang menggerakan seluruh
bisnis virtual ini di seluruh dunia. Artinya, kaum kapitalis memiliki kekuatan
yang sangat besar melebihi kekuatan negara. Disrupsi tidak hanya terjadi dalam
bidang ekonomi saja tetapi dalam semua aspek. Di sini, eksistensi kita sebagai
manusia yang memiliki kebebasan akan sangat mudah ditundukan pada kepentingan
kapitalis. Di dalam pasar kapitalis, manusia hanya akan dianggap sebagai objek komoditas.
Saya
berpikir bahwa fenomena krisis pandemi covid-19 sangat mungkin dijadikan
sebagai kesempatan uji coba ekspansi kapitalis dalam ruang siber secara global,
yang dimaksudkan untuk menggatikan kerja manusia dengan kerja mesin atau untuk
memantau setiap pergerakan individu yang berinteraksi dalam ruang siber. Ekspansi
tersebut bisa saja tidak berakhir di situ. Kapitalis dapat melakukan ekspansi
menembus ruang privat individu-individu yang terlibat di dalam ruang siber
tersebut.
Ada
contoh yang bisa diuraikan berkaitan dengan fenomena ini. Jika kita
memperhatikan sebagian besar aplikasi media sosial seperti, Youtube, Facebook, Instagram
yang awalnya bebas dari iklan sekarang sudah mulai disisipi oleh konten iklan
yang sangat sesuai dengan preferensi kita. Ini berarti pencurian data pribadi telah
terjadi. Perusahan-perusahan itu berhasil membaca data profil tanpa kita sadari
yang kemudian digunakan untuk menyisipkan konten iklan. Hal ini bisa terjadi karena
user tidak pernah peduli dengan persoalan semacam ini. Kebanyakan orang
menggunakan berbagai aplikasi digital tanpa peduli dengan segala dampak yang
ditimbulkan. Selama berguna, aplikasi itu akan terus digunakan. Perilaku
pengguna yang masa bodoh dengan persoalan ini tentu akan memudahkan perusahaan
pemilik aplikasi untuk terus membaca data profil kita hingga bisa mengetahui
semua hal tentang diri kita. Yuval Noah Harari menggambarkan kegelisahan ini
secara gamblang dalam tulisaanya yang berjudul the world after coronavirus.
Ia membuat sebuah eksperimen hipotetis bahwa jika perusahaan dan pemerintah
pada suatu waktu mulai menerapkan pengawasan digital dalam diri kita, mereka dapat
memanen data biometrik secara massal dan dapat mengenal kita jauh lebih baik
daripada diri kita sendiri. Mereka kemudian tidak hanya dapat memprediksi
perasaan tetapi juga mampu memanipulasi perasaan dan menjual apa pun yang sesuai
dengan preferensi kita.[5]
Kedua,
dalam
kaitan dengan hegemoni oligarki. Kemampuan teknologi digital menjadi modal
kapital baru bagi kaum oligark. Satu fakta menggembirakan bagi mereka adalah
perkembangan jumlah pengguna internet yang terus meningkat setiap tahun. Hal
ini dapat digunakan sebagai senjata untuk memanipulasi preferensi publik
terhadap pilihan politik. Di Indonesia, aplikasi Facebook dan Twitter menjadi
aplikasi yang paling populer. Kehadiran dua aplikasi ini tidak hanya mempermudah
pekerjaan dan mengurangi biaya politik tetapi bisa memberi dampak pada hasil
yang maksimal. Hal ini bisa kita telusuri dari fenomena People Power–nya
Jokowi 2014 dan Pilgub Jakarta 2017 di mana partai mengubah preferensi publik
dengan memanfaatkan media sosial.
Perkembangan
ini pada titik tertentu berdampak pada munculnya hoaks. Teknologi tidak hanya
memudahkan orang mengakses informasi tetapi juga melemahkan kesadaran
verifikasi data. Kesempatan ini bisa digunakan oligark sebagai peluang
meningkatkan popularisme politik demi memasok tingkat elektabilitas. Namun,
hoaks yang terjadi tidak hanya menguntungkan oligark tetapi juga mengancam
kehidupan sosial-politik masyarakat. Sebagaimana kemampuan TI dalam menciptakan
real virtuality, hoaks yang terjadi dalam ruang virtual berdampak sampai
dunia nyata. Karena dampaknya yang real ini maka hoaks berkembang menjadi
bisnis yang menggiurkan. Bisnis hoaks dikenal lewat kehadiran buzzer dan
influencer.
Dua aspek di atas memberi gambaran kelam tentang bagaimana fenomena dunia digital menghantam keberadaan manusia yang hidup dalam ruang virtual. Dua aspek itu menjadi penting karena perkembangan teknologi informasi telah memaksa manusia masuk dalam ruang virtual. Manusia kedepannya akan hidup berdampingan dengan dunia digital seperti artificial intelligence, big data, internet of things, dan robotic. Perkembangan teknologi merupakan sebuah keniscayaan. Untuk itu, fenomena ini menuntut manusia menguasai teknologi agar tidak terkena dampak negatifnya. Namun, kecakapan penggunaan teknologi masih belum cukup untuk mengatasi serangan siber. Keamanan data digital masih menimbulkan banyak persoalan. Di samping itu, lemahnya kesadaran verifikasi data menambah banyak persoalan baru. Hoaks menjadi konten informasi yang lebih disenangi publik. Jika kita tidak hidup secara bijak dalam ruang virtual dengan segala kemampuan teknologi digital yang serba canggih, kita tidak akan bisa merasakan manfaatnya. Alih-alih mendapatkan manfaat, kita malah terperangkap dalam ancaman terhadap eksistensi kemanusiaan kita sendiri, seperti hilangnya kebebasan dan privatisasi bahkan kita bisa ditundukan pada mekanisme pasar kapitalis yang menjadikan kita sebagai objek komoditas ekonomi dan bahkan politik.
Di sisi lain, kita bisa saja merayakan kemampuan TI dalam membantu manusia. Manfaat itu dirasakan ketika TI mampu mengahadirkan relasi dan komunitas sosial yang terasa semakin real dalam ruang virtual. Hal ini dapat mempermudah manusia dalam berbagai hal seperti berbagi data secara cepat dan mudah yang bisa melampaui hambatan geografis. Di saat kita berada dalam masa krisis pandemi covid-19, ruang virtual menjadi satu-satunya ruang publik teraman di dunia saat ini. Kita bersyukur atas manfaat besar ini karena jika tidak kita akan akan teralienasi dalam lingkungan sosial kita sendiri.
[1] Budi Hardiman, Ruang Publik:
Melacak Partisipasi Demokrasi dari Polis sampai Cyberspace (Yogyakarta:
Kanisius, 2010), hlm. 329-34.
[2] Yasraf Amir, Posrealitas: Realitas kebudayaan dalam era postmetafisika,
(Yogyakarta: Jalasutra, 2004), hlm. 105-107.
[4] Budi Hardiman, op. it., hlm. 190
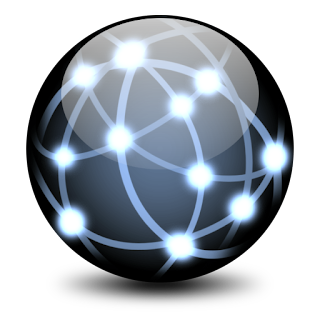
Comments
Post a Comment